Setelah demonstrasi akhir Agustus yang lalu, polisi menangkap beberapa orang. Di antaranya disangka melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946. Mengingat tidak ada ikhtiar serius dari pembentuk undang-undang untuk menerjemahkannya secara otoritatif, rumusan pasal tersebut masih berbahasa Belanda hingga saat ini.
Dalam bahasa Belanda, tindak pidana penghasutan disebut opruiing. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (1983: 70) menerjemahkan, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Selain tidak ada terjemahan resminya, tidak ada juga penjelasan hukum yang otoritatif terhadap unsur-unsur pembentuk Pasal 160 KUHP 1946. Namun, secara doktrinal, Wirjono Prodjodikoro (1986: 151-153), P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2010: 504-523), serta Ahmad Sofian (2019), misalnya, telah memberikan uraian hukum yang memadai, meskipun di beberapa bagian perlu untuk dilengkapi sesuai dengan perkembangan hukum.
Ketiadaan terjemahan serta penjelasan hukum yang otoritatif membuat penegakan hukum terkait tindak pidana penghasutan menjadi subjektif dan problematik. Begitu yang terjadi, misalnya, terhadap perintis kemerdekaan Indonesia, Douwes Dekker atau Setiabudhi. Ia dituduh menghasut untuk melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam suatu pranatan dari Susuhunan Surakarta. Unsur “tindak pidana” dalam tindak pidana penghasutan diperluas, termasuk perbuatan yang diatur dalam pranatan Susuhunan Surakarta (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 152-153).
Secara historis, di Belanda, hanya ada dua macam perbuatan yang diharapkan penghasut, yaitu terjadinya suatu tindak pidana dan perbuatan menyerang kekuasaan umum dengan kekerasan. Namun, di Indonesia, ditambah: tidak menaati suatu peraturan undang-undang. Pertanyaan kritis Wirjono Prodjodikoro (1986: 152): jika alasan perbedaan rumusan tersebut karena hubungan-hubungan kolonial (koloniale verhoudingen), maka apakah dan sampai di manakah Pasal 160 KUHP 1946 itu harus diubah?
Permohonan judicial review terhadap Pasal 160 KUHP 1946 pernah diajukan oleh Rizal Ramli kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun menolak permohonan tersebut, MK melalui putusannya nomor: 7/PUU-VII/2009, tanggal 22 Juli 2009, halaman 73, menegaskan bahwa Pasal 160 KUHP 1946 sebagai tindak pidana (dengan perumusan) materiil, bukan lagi formil.
Pada tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang (Adami Chazawi, 2020: 126). Dengan timbulnya akibat yang dilarang, tindak pidana dengan perumusan materiil dipandang telah selesai (Topo Santoso, 2023: 130). Artinya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan perumusan materiil hanya dapat dilakukan jika akibatnya telah terjadi.
Meskipun para pemikir hukum pidana telah menjelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 160 KUHP 1946 secara memadai dan putusan MK yang mengubah jenis perumusannya, namun belum ada penjelasan hukum tentang kapan perbuatan “melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” dinyatakan menurut hukum telah terjadi. Unsur ini perlu dijelaskan agar memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia (HAM).
Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka. Begitupun menurut Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dalam General Comment Nomor 13 yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 14 ayat (2) KIHSP berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Berdasarkan asas itu, tidak ada seseorang yang dapat dianggap bersalah sampai dakwaan tersebut terbukti tanpa keraguan yang wajar. Artinya, dakwaan terhadap seseorang harus dibuktikan di pengadilan melalui alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, sehingga pemidanaan bukan berdasarkan dugaan semata.
Di Indonesia, jaminan terpenuhinya salah satu asas hukum yang fundamental (Peter Mahmud Marzuki (2020: 47-62)) itu dapat dijumpai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, putusan pengadilan terhadap kesalahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap disebut sebagai terpidana.
Memperhatikan instrumen HAM internasional maupun hukum nasional di atas, tindak pidana dapat disebut telah terjadi dan pelakunya dapat dipidana ketika putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan menggunakan tolok ukur tersebut, maka akibat dari tindak pidana penghasutan harus terlebih dulu diperiksa di pengadilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika tidak demikian, maka tindak pidana penghasutan belum terjadi, mengingat perumusannya yang telah bergeser menjadi tindak pidana dengan perumusan materiil.
Dalam persidangan terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari penghasutan, maka harus dibuktikan secara tegas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dan merupakan tindak lanjut karena pelakunya terhasut. Pembuktian tersebut sangat penting untuk menunjukkan adanya kausalitas antara siapa yang menghasut dengan siapa yang terhasut hingga kemudian melakukan tindak pidana sebagai akibat dari adanya hasutan.
Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, ketiadaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap akibat dari perbuatan menghasut menjadikan penetapan tersangkanya menjadi prematur. Penetapan tersangka tersebut kehilangan legimitasinya, karena tidak terdapat cukup bukti atau bahkan ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika sudah demikian, maka penyidik harus menghentikan penyidikan sebagaimana menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
–
MOCH. CHOIRUL RIZAL adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri serta Direktur Eksekutif dan Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana.
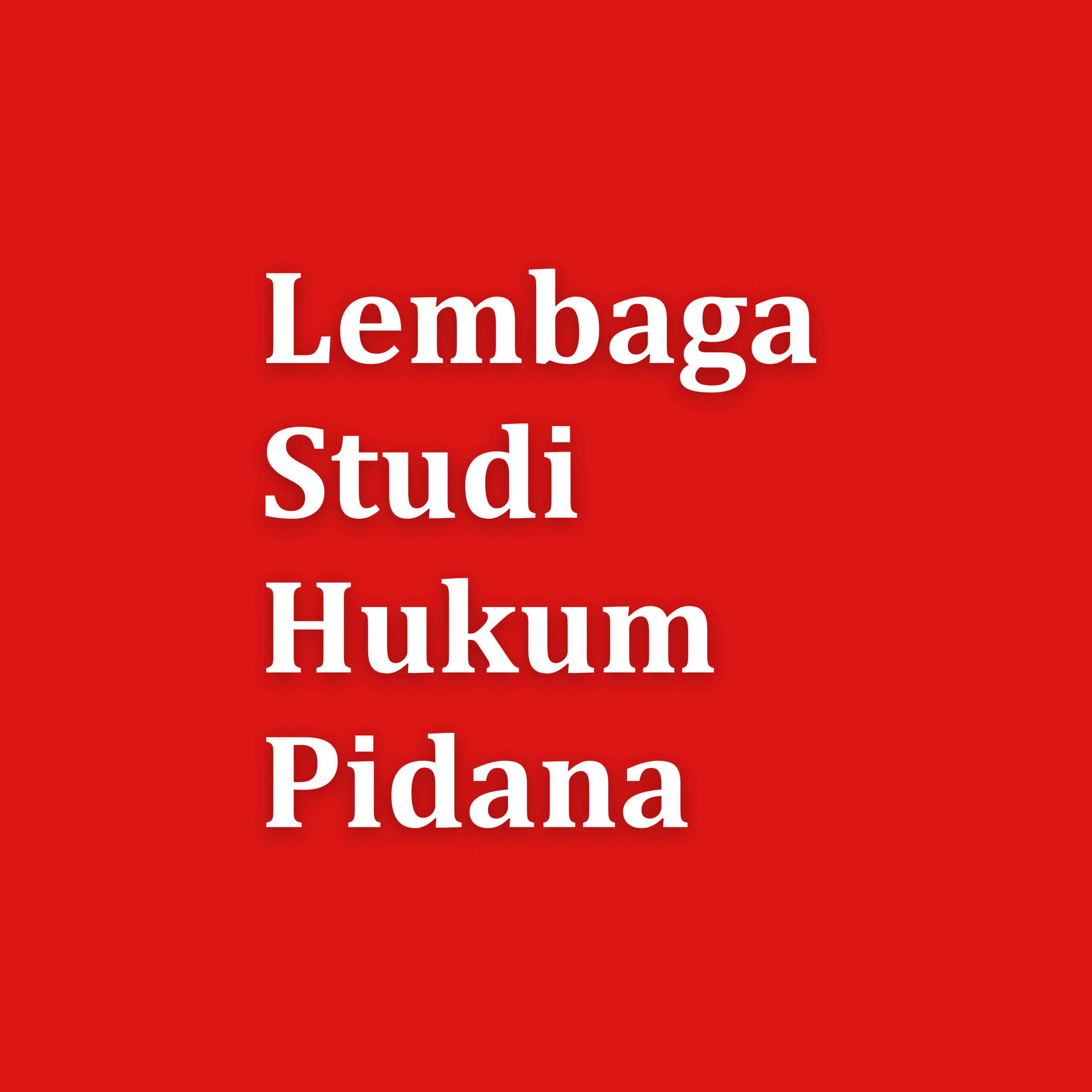
Leave a Reply